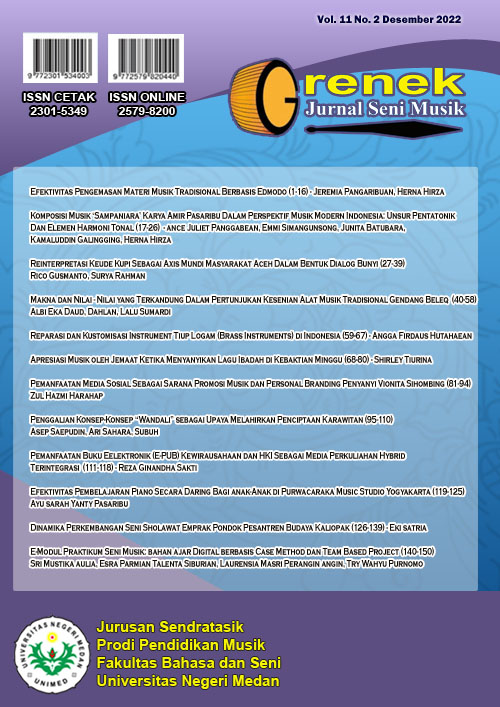Penggalian Konsep-konsep œWandali Sebagai Upaya Melahirkan Model Penciptaan Karawitan
Main Article Content
Abstract
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors published with the Grenek: Jurnal Seni Musik agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Access)
References
Arsola, P., Rafiloza, R., & N, S. (2021). Pacu Itiak Sebagai Sumber Penciptaan Komposisi œSRIPANGGUNG. Grenek Music Journal, 10(2), 1. https://doi.org/10.24114/grenek.v10i2.27428
Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: The Nooday Press.
Barthes, R. (1977). Image Music Text. London: Fontana Press.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Los Angeles: University of Nebraska, Linciln.
Denzin, Norman K, and Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitatif Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fauzi, A., & Widiastuti, U. (2021). Inovasi Instrumen Biola Berfret Di Mts Nurhasanah Kabupaten Batubara. Grenek Music Journal, 9(1), 1. https://doi.org/10.24114/grenek.v9i1.23292
Hastanto, S. (2009). Konsep Pathet Dalam Karawitan Jawa. Surakarta: Program Pascasarjana bekerjasama dengan ISI Press, Surakarta.
Hermawati, S., Arini, D., & Supriadi, Didin, S. (2015). Karakter Musik Etnik dan Represenatsi Identitas Musik Etnik. Panggung Jurnal Seni Dan Budaya, 25(2), 177“188.
Hidayati, R. K. (2016). Makna Tari Bajidor Kahot Ditinjau Dari Teori Semiotika Roland Barthes Semiotics Analysis Bajidor Kahot Dance Seen From Theory Semiotics of Roland Barthes. Promedia, II(2), 64“82.
Ibrahim, M. M. (2019a). Etika Sosial dalam Gending-Gending Karya Ki Narto Sabdo: Vol. (Issue). UIN Walisongo.
Ibrahim, M. M. (2019b). œEtika Sosial Dalam Gending-Gending Karya Ki Narto Sabdo. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
Joseph, J. E. (2004). œThe Linguistic Sign, in The Gembrige Companion to Saussure. New York: Cambrideg University Press.
Karina, A. E., Rozak, A., & Sari, F. D. (2020). Alih Kreativitas Pelaku Seni Kabupaten Bireuen Sebagai Peluang Pendapatan di Tengah Wabah COVID-19 ( StudiI Kasus : NIZAR 41 Project Official ). Grenek: Jurnal Seni Musik, 9(2), 108“120.
Logie, J. (2013). 1967: The birth of œthe death of the author. College English, 75(5), 493“512.
Marsudi. (1998). œCiri Khas Gending - gendhing Ki Narto Sabdo: Kajian Musikologi Karawitan. PPS UGM Yogyakarta.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sahara, A. (2022). Analisis Bentuk dan Struktur Garap Geding Wandali Karya Ki Nartosabdo. Jurusan Karawitan FSP ISI Yogyakarta.
Satria, E. (2022). Aransemen Sholawat Syi™ir Tanpo Waton: Sebuah Proses Kreatif. Grenek Music Journal, 11(1), 55. https://doi.org/10.24114/grenek.v11i1.34789
Saussure, F. de. (1915). Course in General Linguistics, Translate by Roy Harris. London: Bloomsbury.
Suardi, D. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. In Metode Penelitian Kualitatif (Issue 17). http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf
Sumanto. (1990). Nartosabdo Kehadirannya Dalam Dunia Pedalangan : Sebuah Biografi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Sumardjo, J. (2000). Filsafat Seni. Bandung: Penerbit ITB.
Supanggah, R. (2009a). Bothekan Karawitan II: Garap. Surakarta: ISI Press.
Supanggah, R. (2009b). Bothekan Karawitan II: Garap. Surakarta: ISI Press.
Suparli, L. (2010). Gamelan Pelog Slendro: Induk Teori Karawitan.
Bandung: Sunan Ambu Press.
Suparli, L., Arini, D., & Supriadi, D. (2015). Karakter Musik Etnik. Panggung Jurnal Seni Dan Budaya, 25(2), 177“188.
Supriadi, D. (2001). Kreativitas, Kebudayaan dan Perkembangan Iptek. Bandung: Alfabeta.
Waridi in Supanggah. (2009). Bothekan Karawitan II:Garap. Surakarta: ISI Press.